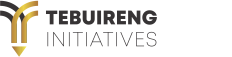Ibadah udḥiyah (kurban) merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, khususnya saat memasuki bulan Dzulhijjah. Anjuran pelaksanaan udḥiyah ini telah banyak disebutkan dalam berbagai literatur keislaman klasik maupun kontemporer, yang menunjukkan betapa pentingnya kedudukan ibadah ini dalam syariat. Bahkan, karena urgensinya, syariat juga memberikan sejumlah adab dan ketentuan tambahan bagi mereka yang berniat melaksanakan udḥiyah. Salah satu di antaranya adalah anjuran untuk tidak memotong kuku maupun rambut sejak masuknya bulan Dzulhijjah hingga hewan kurban disembelih. Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi ﷺ sebagai bentuk keserupaan dengan jamaah haji yang sedang berihram, serta sebagai manifestasi kesiapan ruhani dalam menyambut ibadah besar ini.
Dalam literatur fikih empat mazhab, perbedaan pendapat mengenai hukum memotong kuku atau rambut bagi orang yang hendak berkurban pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah bermuara pada perbedaan cara memahami hadis riwayat Ummu Salamah. Hadis tersebut berisi larangan bagi seseorang yang ingin berkurban untuk tidak mengambil (memotong) rambut dan kukunya sejak awal Dzulhijjah hingga pelaksanaan kurban. Berikut teks hadisnya
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»
Diriwayatkan dari Ibnu Abi ‘Umar al-Makki, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari ‘Abd al-Rahman bin Humaid bin ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf, ia mendengar Sa‘id bin al-Musayyib menceritakan dari Ummu Salamah, bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Apabila telah masuk sepuluh hari (awal Dzulhijjah), dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia menyentuh (memotong) sedikit pun dari rambut dan kulitnya.” (Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Naysābūrī, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi-Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūl Allāh ṣallā Allāhu ‘alayhi wa sallam, )Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, tt(. Juz 5, hlm 156.)
Dalam kitab Al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī wa Huwa Sharḥ Mukhtaṣar al-Muzanī karya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan dan pemaknaan hadis ini, yang pada akhirnya membentuk tiga pandangan utama di kalangan mazhab-mazhab fikih: Pertama, menurut Mazhab Syafi‘i, hadis tersebut dipahami sebagai anjuran (istihbāb), bukan kewajiban.
Artinya, seseorang yang berniat berkurban disunnahkan untuk tidak mengambil rambut dan kukunya selama sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun, apabila ia tetap melakukannya, maka hukumnya makruh, tetapi tidak sampai pada tingkat keharaman. Pendapat ini juga dinisbatkan kepada Sa‘id ibn al-Musayyib, seorang tabi‘in terkemuka.
Kedua, menurut Imam Ahmad ibn Hanbal dan Ishaq ibn Rahuyah, larangan dalam hadis tersebut dipahami sebagai sesuatu yang wajib, sehingga orang yang hendak berkurban haram hukumnya memotong rambut dan kukunya selama waktu tersebut. Mereka memahami larangan ini berdasarkan zahir hadis dan analoginya dengan kondisi orang yang sedang berihram dalam ibadah haji.
Ketiga, Mazhab Hanafi dan Maliki memandang bahwa larangan tersebut tidak termasuk sunnah, dan tidak makruh untuk mengambil rambut dan kuku bagi orang yang akan berkurban. Mereka beralasan bahwa orang tersebut tidak dalam keadaan ihram, sehingga tidak ada pengharaman atasnya sebagaimana orang lain yang tidak akan berkurban. Selain itu, mereka juga berargumen bahwa karena penggunaan wewangian dan pakaian tidak diharamkan, maka memotong rambut pun tidak seharusnya dilarang.
Penjelasan yang dikemukakan dalam berbagai literatur turats oleh para ulama salaf umumnya menafsirkan hadis tersebut dalam konteks larangan atau kebolehan memotong rambut dan kuku dari anggota tubuh orang yang hendak melaksanakan ibadah udhiyah.
Pemahaman ini dilandasi oleh pengembalian dhamir ه dalam kata شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ (rambut dan kulitnya) kepada lafaz أَحَدُكُمْ dalam hadis, yang merujuk pada mudahhi (orang yang berkurban). Oleh karena itu, para ulama tersebut menyimpulkan bahwa larangan atau kebolehan tersebut berkaitan dengan tindakan menghilangkan rambut atau kuku yang berasal dari tubuh orang yang berniat berkurban selama sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.
Imam An-Nawawi dalam al-Majmū’ menjelaskan bahwa salah satu hikmah di balik anjuran untuk tidak memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah agar seluruh anggota tubuh orang yang hendak berkurban kelak diselamatkan dari siksa api neraka.
Hal ini berpijak pada keyakinan bahwa ibadah kurban memiliki keutamaan sebagai bentuk penghapus dosa dan perlindungan dari azab. Selain itu, sebagian ulama juga memandang bahwa larangan ini menyerupai ketentuan bagi orang yang sedang berihram, di mana selama masa ihram, seorang Muslim juga tidak diperkenankan memotong rambut dan kuku, namun pandangan ini mendapatkan suatu penolakan dari mayoritas murid ulama di saat itu, hal ini kemudian disampaikan imam An-Nawawi dalam kitabnya, berikut pernyataan lengkap beliau
قال أصحابنا الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار وقيل للتشبه بالمحرم قال أصحابنا وهذا غلط لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم والله أعلم
Para ulama dari kalangan mazhab kami (Syafi‘iyyah) menjelaskan bahwa hikmah dari larangan memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban adalah agar tubuhnya tetap utuh, sehingga seluruh anggota badannya dapat terbebas dari api neraka sebagai bentuk pelepasan (ʿitq) dari siksa. Ada juga yang berpendapat bahwa larangan tersebut bertujuan untuk menyerupai orang yang sedang berihram. Namun para ulama kami menilai bahwa pendapat ini kurang tepat (ghalaṭ), karena orang yang hendak berkurban tidak diharuskan meninggalkan hal-hal lain yang diharamkan bagi orang yang ihram seperti memakai wewangian, dan pakaian yang berjahit. (Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab, cet. ke-1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/1997 M). Juz 8, Hlm 392.)
Meskipun mayoritas ulama dari kalangan empat mazhab telah sepakat bahwa khitab dalam hadis terkait memotong kuku dan rambut selama sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah ditujukan kepada bagian tubuh orang yang hendak berkurban (mudahhi), yakni larangan atau kebolehan menghilangkan kuku dan rambutnya sendiri, namun terdapat pandangan berbeda dari sebagian ulama.
Menurut pendapat ini, dhamir ه pada lafaz شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ dalam hadis tersebut tidak kembali kepada أَحَدُكُمْ (salah satu dari kalian yang hendak berkurban), melainkan kembali kepada hewan yang akan dikurbankan. Dengan demikian, yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah larangan mencukur rambut dan kuku orang yang berkurban, tetapi larangan menghilangkan bagian tubuh hewan kurban sebelum disembelih. Pendapat ini salah satunya disampaikan Ibn Malak, seorang ulama yaang bermadzhab hanafi dalam salah satu kitabnya, berikut teks lengkapnya
فلا يمسن من شعره ؛ أي: من شعر ما يضحي به. وبشره ؛ أي: ظفره
Maka jangan menyentuh (menghilangkan) sedikit pun dari rambutnya, maksudnya adalah rambut hewan yang akan dikurbankan. Dan ‘kulitnya’ maksudnya adalah kuku dari hewan yang akan dikurbankan.(Ibn al-Malak, Syarḥ Maṣābīḥ al-Sunnah li al-Imām al-Baghawī, cet. ke-1, )Idārah al-Thaqāfah al-Islāmiyyah, 1433 H/2012 M(. Juz 2, Hlm 263)
Ali bin Muhammad al-Qari dalam kitabnya Mirqāt al-Mafātīḥ, Mulla ‘Alī al-Qārī memberikan tanggapan kritis terhadap pendapat Ibnu al-Malak yang menafsirkan larangan dalam hadis Ummu Salamah sebagai larangan terhadap pemotongan rambut dan kuku hewan kurban, bukan terhadap pelaku kurban (mudahhi). Menurut Mulla Al-Qārī, pandangan Ibnu al-Malak ini tergolong gharīb (langka dan menyendiri) karena tidak ditemukan adanya ulama lain yang mendukung tafsiran semacam itu.
Meskipun pendapat Ibn Malak tergolong langka, namun pandangannya memperoleh dukungan dari salah satu ulama kontemporer, KH. Ali Mustafa Yaqub. seperti yang tercantum dalam karyanya yang berjudul At-Turuqus Shahihah fi Fahmis Sunnatin Nabawiyah.
Menurutnya, untuk memahami makna larangan dalam hadis riwayat Ummu Salamah diperlukan pendekatan komparatif melalui pemahaman hadis-hadis lain yang masih satu tema. Hal ini berlandaskan pada teori dalam disiplin fiqih hadis (fiqhul ḥadīṡ) yang dikenal dengan istilah wiḥdat al-mawḍūʻiyyah fī al-ḥadīṡ (kesatuan tema dalam hadis).
Teori ini bertujuan untuk menyingkap ‘illat atau maksud hukum dari suatu hadis, khususnya ketika dalam satu riwayat tertentu tidak disebutkan secara eksplisit sebab (‘illat) atau hikmah suatu larangan atau perintah. Oleh karena itu, perlu dikomparasikan dengan hadis lain yang lebih spesifik, meskipun tetap dalam satu konteks pembahasan, oleh karena itu ia sering menegaskan bahwa Al-hadits yufassiru ba’dhuhu ba’dhan (hadits saling menafsirkan antara satu dengan lainnya).
KH. Ali Mustafa Yaqub mengategorikan kasus pemahaman terhadap larangan dalam hadis Ummu Salamah ini sebagai bentuk mubham al-ḥadīṡ (hadis yang maknanya belum jelas atau samar). Dalam konteks ini, pendekatan melalui wiḥdat al-mawḍūʻiyyah menjadi sangat penting untuk menghilangkan kemubhaman tersebut dan memperoleh pemahaman yang utuh dan objektif terhadap makna hadis. Dalam upayanya ia mengkomparasikan hadis Riwayat Ummu salamah dengan hadis Riwayat Aisyah yang diriwayatkan imam at-Tirmidzi berikut
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا»
Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar (Idul Adha) yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih (hewan kurban). Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat beserta tanduknya, bulunya, dan kukunya. Dan sungguh, darah hewan kurban itu akan sampai kepada (keridhaan) Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka, relakanlah (ikhlaskanlah) penyembelihan itu dengan hati yang lapang.”
Berdasarkan kajian terhadap hadis yang diriwayatkan Aisyah di atas, KH. Ali Musthafa Yaqub mengambil kesimpulan bahwa larangan dalam hadis Ummu Salamah tersebut sejatinya tidak ditujukan kepada rambut dan kuku orang yang hendak berkurban, melainkan kepada rambut dan kuku hewan kurban itu sendiri.
Hal ini didasarkan pada hikmah bahwa bagian-bagian tubuh hewan kurban seperti rambut, kuku, dan tanduk akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Riwayat Aisyah di atas. Oleh karena itu, menurutnya, larangan untuk tidak memotong rambut dan kuku lebih tepat ditujukan kepada hewan kurban, bukan kepada orang yang berkurban. Kiai Ali menegaskan
فالعلة في تحريم قطع الشعر والأظافر ليكون ذلك شاهدا لصاحبها يوم القيامة وهذا الإشهاد إنما يناسب إذا كان المحرم من القطع شعر الأضحية وأظافرها، لا شعر المضحى
’Illat larangan memotong rambut dan kuku ialah karena ia akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Hal ini tepat bila dikaitkan dengan larangan memotong bulu dan kuku hewan kurban, bukan rambut orang yang berkurban.”
Meski demikian, Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah RA yang menjadi acuan kyai Ali dalam mengkomparasikan pemahaman larangan memotong rambut dan kuku di atas, dinilai lemah oleh mayoritas ulama hadis. Sebab utama kelemahannya terletak pada salah satu perawi dalam sanadnya, yaitu Abu al-Mutsanna, yang bernama lengkap Sulaiman bin Yazid al-Laitsi.
Para ahli hadis menganggapnya sebagai perawi yang tidak kuat hafalannya dan sering kali menyelisihi riwayat perawi-perawi yang lebih terpercaya. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Taqrib at-Tahdzib menyebutnya secara tegas: “Abu al-Mutsanna al-Khuza’i, namanya Sulaiman bin Yazid, perawi yang dha’if (lemah), dari generasi keenam.” Penilaian serupa juga datang dari Imam Ibnu Hibban yang memasukkan namanya dalam kitab al-Dhu’afa’, sebuah karya khusus yang membahas para perawi yang dinilai lemah. Bahkan Imam al-Baghawi dalam Syarh as-Sunnah juga memberikan isyarat atas kelemahan perawi ini.
Senada dengan al-Baghawi, Imam al-Dzahabi dalam Talkhish al-Mustadrak menanggapi dengan mengatakan: “Sulaiman dha’if (lemah), bahkan sebagian ulama meninggalkannya.” Demikian pula al-Mundziri dalam at-Targhib wa at-Tarhib menjelaskan bahwa sanad hadis ini melalui Sulaiman bin Yazid dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, namun ia menegaskan bahwa Sulaiman dikenal lemah, meskipun ada yang pernah memberikan penilaian baik kepadanya. (Khalid bin Dhaifullah asy-Syalahi, Raudhatul Mutamatti‘ fi Takhrij Ahadits ar-Raudh al-Murbi‘, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, Cet. 1, 1440 H / 2019 M). Juz 3, Hlm 662)
Dengan memperhatikan penilaian mayoritas ulama hadis terhadap hadis riwayat Aisyah yang menyebutkan bahwa rambut, kuku, tanduk, dan bulu hewan kurban akan menjadi saksi di hari kiamat timbul satu kemusykilan metodologis jika hadis ini dijadikan sebagai mubayyin (penjelas) bagi hadis riwayat Ummu Salamah tentang larangan memotong kuku dan rambut bagi orang yang hendak berkurban.
Pasalnya, hadis Ummu Salamah memiliki status sahih, sementara hadis riwayat Aisyah tersebut dinilai dhaif (lemah) oleh sebagian besar ahli hadis. Hal ini menimbulkan kejanggalan, sebab tidak lazim jika sebuah hadis yang lemah dijadikan sebagai penjelas bagi hadis yang sahih.
Dalam tradisi keilmuan para ulama, baik dari kalangan salaf maupun mutaakhirin, terdapat kesepakatan bahwa hadis dhaif dapat dijadikan acuan dalam beberapa kondisi tertentu. Salah satunya adalah ketika hadis dhaif tersebut berfungsi sebagai penjelas (mubayyin) terhadap hadis sahih yang mengandung makna umum atau multitafsir (ihtimal).
Dalam hal ini, hadis dhaif dianggap valid untuk memperjelas maksud dari hadis sahih tersebut, selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah utama dalam ilmu hadis dan ushul fiqh. Contoh penerapannya dapat dilihat pada penggunaan hadis riwayat Aisyah sebagai penjelas terhadap hadis riwayat Ummu Salamah yang melarang orang yang hendak berkurban untuk memotong kuku dan rambutnya.
Meski status hadis Aisyah tergolong dhaif, namun karena makna hadis Ummu Salamah bersifat umum dan memungkinkan beberapa penafsiran, maka ulama memperkenankan penggunaan hadis Aisyah sebagai penjelas. Pandangan ini di antaranya ditegaskan oleh Syekh Muhammad Awwamah dalam karyanya Atsaru al-Hadis al-Syarif Fi Ikhtilafi ‘Aimmah al-Fuqaha
وللعمل بالحديث الضعيف مجال آخر، هو : إذا عرض حديث يحتمل لفظه معنيين دون ترجيح بينهما، وورد حديث ضعيف يرجح أحدهما، فحينئذ نأخذ بالمعنى الذي يُرجّحه هذا الحديث ولو كان ضعيفاً، كما نص على ذلك عدد من الأئمة السابقين واللاحقين
Ada pula ruang lain untuk mengamalkan hadis yang lemah, yaitu: ketika ada suatu hadis yang lafaznya mengandung dua makna yang memungkinkan, tanpa ada unsur yang menguatkan salah satunya. Kemudian datang sebuah hadis lemah yang menguatkan salah satu dari dua makna tersebut, maka dalam kondisi seperti ini, kita mengambil makna yang dikuatkan oleh hadis lemah itu meskipun statusnya lemah. Hal ini telah ditegaskan oleh sejumlah imam dari kalangan ulama terdahulu maupun yang belakangan.
Dengan demikian, pemahaman yang paling mendekati maksud dari larangan memotong kuku dan rambut dalam hadis riwayat Ummu Salamah adalah larangan terhadap pemotongan kuku dan rambut hewan kurban, bukan kuku dan rambut orang yang berkurban (mudahhi).
Kesimpulan ini diperoleh melalui pendekatan komparatif antara hadis Ummu Salamah dan hadis Aisyah, di mana hadis Aisyah berfungsi sebagai penjelas (mubayyin) atas hadis Ummu Salamah, meskipun status hadis Aisyah termasuk dhaif. Namun, hal ini tidak serta-merta menegasikan pendapat para ulama salaf yang memahami larangan dalam hadis tersebut sebagai larangan bagi orang yang hendak berkurban untuk memotong kuku dan rambutnya.
Pandangan tersebut tetap memiliki landasan kuat, karena lahir dari hasil ijtihad. Dan sebagaimana diketahui dalam kaidah ushul fikih, pendapat yang lahir dari ijtihad tidak dapat secara mutlak dikatakan benar atau salah. Setiap pandangan memiliki proses dan metodologi istinbath-nya masing-masing, sehingga semuanya layak untuk dihormati dalam khazanah keilmuan Islam. Wallahua’lam
Penulis: Ma’shum Ahlul Choir, Mahasantri M2 Ma’had Aly Hasyim Asy’ari
Editor: Thowiroh