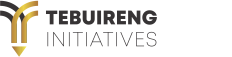Di balik ketenangan Kecamatan Gudo, Jombang, terdapat kisah panjang tentang perantauan, dari Negeri Tirai Bambu. Sekilas, Gudo hanya tampak seperti wilayah kecil biasa di tengah Jawa Timur. Namun, siapa sangka, dari wilayah tersebut menjadi titik penting dalam sejarah datangnya Tionghoa ke Indonesia. Kisah ini bermula pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perantau dari Tiongkok Selatan meninggalkan tanah kelahiran mereka karna adanya pergolakan politik dan ekonomi.
Mereka menyeberangi lautan, menempuh perjalanan panjang yang penuh risiko selama tiga bulan, dengan harapan bisa membangun hidup baru di bumi Nusantara. “Mereka itu datang tidak membawa apa-apa, hanya semangat dan patung dewa yang mereka bawa untuk perlindungan selama pelayaran,” ujar Ibu Nanik, pengurus harian Klenteng Gudo.
Para perantau itu menyebar ke berbagai wilayah, namun Gudo menjadi salah satu tempat untuk mereka menetap. Letaknya yang tidak berada di pesisir, tetapi justru di pedalaman, menjadi daya tarik tersendiri karena kesuburan tanahnya.
“Kenapa mereka ke Gudo? Padahal Gudo kan ndeso, bukan kota besar,” ucap Bu Nanik sambil tertawa kecil, mengenang cerita para leluhur. Ia menjelaskan bahwa Gudo memiliki keunggulan geografis, yaitu berada di perbatasan Jombang dan Kediri, dipisahkan oleh kali konto.
Di sepanjang sungai tersebut, sejak abad ke-19 telah dibangun 70 pintu air yang dikenal dengan sebutan Rolak Pitung Puluh. Sistem irigasi ini membuat lahan pertanian di Gudo tetap subur, tidak banjir saat musim hujan dan tidak kekeringan saat musim kemarau. “Kalau tanahnya subur, pasti orang ingin menetap. Itu naluri,” katanya meyakinkan.
Seiring waktu, Gudo menjadi kawasan yang hidup. Di masa kolonial, berdiri pabrik gula dan pengolahan tembakau, yang menyerap banyak tenaga kerja. Para perantau Tionghoa yang tidak memiliki modal berdagang, akhirnya bekerja di pabrik tersebut sebagai tukang masak dan buruh.
Bahkan, di belakang Klenteng ada sebuah desa yang dikenal sebagai Desa Tukangan, karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai tukang di pabrik gula. “Kakek saya juga tukang masak di pabrik gula Cukir,” cerita Bu Nanik. Dari sini, akar komunitas Tionghoa mulai tumbuh kuat di Gudo.
Klenteng menjadi titik pusat dari segala aktivitas komunitas. Pada awalnya, patung dewa yang mereka bawa dari Tiongkok hanya diletakkan di sebuah bangunan sederhana, hanya ditutupi dinding yang terbuat dari bambu agar tidak kehujanan dan kepanasan. Itu semua dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada patung dewa yang mereka bawa karena telah memberikan perlindungan selama perjalanan menuju bumi nusantara.
“Dulu, kami menyebutnya Omah Blek, bukan klenteng,” kenang Bu Nanik. Seiring waktu, seorang dermawan yang hingga kini tidak diketahui Namanya membantu membangun bangunan permanen sebagai bentuk penghormatan pada kepercayaan yang mereka bawa. Kini, klenteng tersebut berdiri megah dan menjadi simbol keteguhan iman para umat Tionghoa.
Nama “Gudo” sendiri ternyata berasal dari kata “Kutau”, yang dalam bahasa Tionghoa berarti kota kecil tua. Karena lidah orang Jawa sulit mengucapkan “Kutau”, maka lama-lama berubah menjadi “Gudo”.
“Jadi Gudo itu bukan berarti penggoda, ya, seperti yang sering dikira orang,” Bu Nanik menjelaskan sambil tersenyum . Dari perubahan bunyi itu, kita bisa melihat bagaimana budaya Tionghoa berasimilasi secara alami dengan bahasa dan kehidupan masyarakat lokal. Gudo bukan hanya rumah bagi umat Tionghoa, tapi juga ruang pertemuan antar budaya.
Klenteng tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga ruang sosial yang terbuka bagi semua kalangan. Bu Nanik menyebutkan, sejak kecil ia dan teman-temannya bermain di halaman klenteng.
“Kami main di sini, besar di sini. Setelah sembahyang ya nongkrong, ngobrol, ketawa-ketawa,” ceritanya penuh nostalgia. Kini, meski usia bertambah, klenteng masih menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi, mulai dari urusan pernikahan, kematian, hingga bakti sosial. “Kami nggak ikut partai politik, tapi kami ikut serta dalam kehidupan masyarakat,” tambahnya.
Spirit keterbukaan ini juga tercermin dari arsitektur klenteng. Pilar-pilar depan dan dalam berjumlah empat, melambangkan empat penjuru mata angin. Ini menandakan bahwa siapapun, dari arah manapun, diterima dengan niat yang baik.
Di depan klenteng terdapat sepasang patung Kilin, makhluk mitologis suci yang hanya muncul pada saat-saat tertentu seperti kelahiran seoran nabi di suatu negara. Patung ini melambangkan keseimbangan antara unsur Yin dan Yang.
Patung laki-laki membawa bola, unsur nya Yang artinya Positif. Sedangkan patung perempuan membawa anak, unsurnya Yin artinya negatif. “Bukan berarti perempuan negatif, ya. Itu simbol keseimbangan antara jasmani dan rohani,” jelas Bu Nanik penuh makna.
Setiap bagian dari klenteng memiliki simbol dan nilai filosofis. Warna merah melambangkan keberanian dan kebahagiaan, sementara kuning melambangkan kemuliaan dan penghormatan. “Makanya Kaisar di Tiongkok dulu pakai baju warna kuning,” kata Bu Nanik, menjelaskan konteks warna dalam budaya Tionghoa.
Di altar utama, umat tidak langsung menyembah dewa, melainkan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Tuhan itu tidak terlihat, tidak terdengar, tapi ada. Itu prinsip kami,” tegasnya.
Banyak yang tidak tahu bahwa klenteng melayani tiga ajaran: Konghucu, Budha, dan Tao. Karena itu, jumlah dewa di dalamnya banyak, masing-masing mewakili nilai-nilai kebaikan seperti keadilan, keberanian, kasih sayang, dan kesenian.
“Kami punya Dewa Pendidikan, Dewa Dagang, bahkan Dewa Kesenian,” kata Bu Nanik sambil menyebutkan beberapa nama seperti Dewi Kwan Im (Dewi Welas Asih) dan Dewa Kongco Kong Tek Cun Ong (Raja Pemberim Berkat). Ia menambahkan bahwa para dewa dulunya adalah manusia bijaksana yang dimuliakan karena jasa dan kebajikannya. “Itu bentuk kami menghormati budi, dan menjadikannya teladan.” Tegas ibu nanik.

Tradisi pun tidak berhenti di altar. Di atas bangunan klenteng terdapat tiga patung dewa yang memiliki nama Fu, Lu, dan Shou. Dewa fu adalah Dewa Pemberi Rezeki, Dewa Lu adalah Dewa Kesejahteraan dan Dewa Shou adalah Dewa Panjang Umur.
Dalam sembahyang, umat membawa buah-buahan sebagai simbol harapan dan syukur. Apel melambangkan kedamaian, pir untuk panjang umur, dan jeruk untuk rejeki. Tidak hanya ketiga buat itu, semua buah boleh dijadikan sajian untuk dewa tersebut, asalkan jangan buah yang memiliki duri seperti, durian dan salak.
“Yang berduri jangan dibawa, ya, karena itu melukai simbol,” terang Bu Nanik. Di Gudo, akulturasi terasa nyata: bunga yang dipersembahkan pun bukan hanya melati atau mawar, tapi juga kenanga dan gading—jenis bunga yang umum dalam budaya Jawa.
Kini, gaya hidup umat pun bertransformasi mengikuti zaman. “Anak-anak sekarang suka Korea, jadi kadang make up dan bajunya ya ala K-pop,” kata Bu Nanik sambil tertawa.
Namun, esensi spiritual tetap dijaga. Umat berusaha meneladani sifat para dewa, terutama Dewi Kwan In yang dikenal sebagai lambang kasih sayang dan pengampunan. “Kalau kita menghormati Kwan In, ya harus bisa memaafkan dan sayang sama orang lain juga,” tambahnya bijak.
Struktur organisasi klenteng pun sudah ada sejak awal 1900-an, lengkap dengan ketua, bendahara, sekretaris, dan notulen kegiatan. Namun, semua pelayanan dilakukan secara sukarela. “Kami tidak mencari keuntungan, kami hanya ingin melayani,” tutur Bu Nanik. Bahkan, jika ada umat dari luar yang ingin terlibat, mereka diterima dengan tangan terbuka. Klenteng Gudo telah menjadi ruang spiritual sekaligus rumah sosial bagi banyak kalangan.
Klenteng ini bukan sekadar bangunan ibadah, melainkan monumen hidup dari perjuangan, toleransi, dan cinta terhadap budaya. Dari Omah Blek sederhana hingga bangunan megah yang terbuka bagi semua, kisah Klenteng Gudo adalah kisah tentang bertahan dan berbagi. Iman, budaya, dan masyarakat menyatu dalam ruang yang harmonis. “Kami ini Tionghoa, tapi juga Jawa. Kami belajar hidup berdampingan,” tutup Bu Nanik dengan senyum damai.
Penulis: Novia Dwi Astuti, Mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Universitas Hasyim Asy’ari
Editor: Thowiroh
Baca juga: Gus Ipang Wahid dan Strategi Branding Unhasy di Era Digital